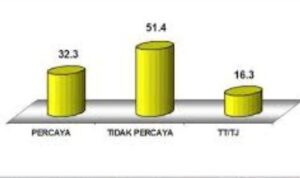MINANGGLOBAL.ID, Khazanah – Setidaknya sejak 2009 saya mulai beransur-ansur menelaah manuskrip kuno. Selama belasan tahun, terhitung 2009-2024, saya belum menemukan teks manuskrip kuno yang menggunakan istilah “buya” untuk seorang ulama, di kampung halaman saya. Panggilan kepada ulama senior, sepuh, biasa dipanggil dengan “Ayah” (maksudnya ayah rohani), sedangkan asisten-asisten guru, yang dikenal dengan Guru Tuo, biasa dipanggil dengan “Angku” (berasal dari kata tuangku). Populernya kalimat “buya” sebagai panggilan, setidaknya masyhur pada sosok Hamka (Haji Abdul Malik Abdul Karim Amarullah), seorang mubaligh ternama asal Maninjau, pengarang ulung, dan pujangga Indonesia.
Lama saya memikirkan makna kata “buya”. Satu saat terbersitlah dari kira-kiraan saya, bahwa kata “buya” berasal dari “اب”, yang bermakna ayah, kemudian ditashghirkan, lalu dibaca dengan model berbeda dari betuk shighatnya, maka jadikan kata “Abuya”, yang kemudian dibaca “Buya”, yang maknanya “ayah tersayang” (disclaimer: kata “buya” yang musytaq dari kata اب itu akal-akalan saya saja, tidak tentu benar). Berdasarkan ini, dua anak gadis saya, sejak kecil saya ajari memanggil saya “buya”, agar terlihat romantis, bukan dengan makna seorang ulama yang betul-betul berilmu dan lurus perilaku.
Saya mulai dipanggil orang buya, setelah saya mulai rajin diundang berceramah dimana-mana, yaitu sejak 2016, dua tahun setelah saya pulang dari perantauan menyelesaikan magister. Walaupun sudah tampil berpidato sejak kecil-kecil, namun saya baru tampil ke atas mimbar setelah mulai agak dewasa. Dalam berceramah, saya juga tidak mau membranding diri; flayer-flayer ceramah yang kadang saya post itu murni buatan pihak kedua, yaitu lembaga, pengurus mesjid, atau panitia acara. Ketika mulai dipanggil “buya” itu terasa berat “pundak”, mengapa tidak? Segala hal ihwal kebaikan disematkan pada kita, dan segala keburukan tentu tidak terbayang pada pribadi kita. Terkenanglah diri, secara jiwa belumlah stagnan, muda belia; ilmu kurang, dosa banyak, belum pantas untuk kalimat itu. Namun saya tidak kuasa menahan orang-orang yang membahasakan saya “buya”. Saya mendengar cerita, di sebuah lembaga pendidikan tradisional, dulu, yang boleh dipanggil buya itu adalah pendirinya saja. Usianya sudah sepuh, tunjuk ajarnya berbekas, dan kebijaksaan betul ada pada jiwanya.
Saya termasuk orang yang tidak suka dikultuskan, baik dalam panggilan dan sikap. Dalam kegiatan-kegiatan saya mencoba tampil sederhana, agar tidak terbebani diri. Saya tidak suka orang menunduk-nunduk kepada saya. Bila ada yang memuji saya berlebih pasti saya tidak respek pada orang itu. Saya juga kurang suka sisa minum saya diperebutkan anak siak. Saya lebih suka apa adanya. Ada orang-orang yang datang ke rumah, saya yang membuatkan teh dan kopinya. Jika ada nampak anak didik saya, saya berusaha terlebih dahulu datang menyalaminya. Jujur, saya tidak suka melihat orang yang mencium tangan bolak balik, kepada seseorang. Kalau satu sisi saja, yaitu punggung tangan, itu sah. Tapi kalau, dalam perut tangan, rasa saya berlebihan. Karena begitu ajaran diterima di surau-surau di kampung saya. Ta’zhim tidak selalu ditunjukkan dengan sikap menunduk, tapi rasa hormat dalam jiwa, dan perhubungan batin yang tidak putus. Bagi saya, secara personal, kata “buya” memberikan ruang untuk perhormatan lebih, dan itu belum pantas bagi saya. Dan baru saya ungkapkan hari ini.
Kata “buya” saat ini sudah menjadi mainan saja, sebab siapapun mudah menyematkan kata buya. Bahkan ada orang tertentu, saya perhatikan, membranding dirinya dengan kata “buya”. Wallahu a’lam apa niatnya. Seorang yang berpakaian seperti orang taat dipanggil buya. Kata-kata sapaan, antara mahasiswa di kampus, kadang sudah biasa mereka ber-buya. Di simpang, tempat ojek, ada yang biasa azan di mesjid, dipanggil buya. Penceramah, buya. Pakai peci, buya. Pakai atribut ke mesjid, buya. Sudah sangat lumrah. Padahal, semestinya panggilan buya itu sakral. Buya, apabila seseorang tua secara umur, dan juga tua secara ilmu, memiliki kebijaksaan, betul-betul menjadi suluh di tengah masyarakat. Bukan sekedar “rancak di labuah” saja.
Demi merenung, mengingat semua, saya kemudian memutuskan tidak ingin dipanggil buya, setidaknya hingga saya melewati 40 tahun, masa stagnan itu. Umur saya belum. Ilmu kurang. Dosa banyak. Sekedar pintar bicara dan bercerita saja. Cukup panggil saya “Angku Mudo/ Ongku Mudo”, karena gelar inilah yang diberikan guru saya tahun 2013 silam. Angku Mudo, bermakna mubtadi’, yang baru-baru mulai menapak di jalan kepada Allah. Mungkin inilah refleksi untuk diri saya, melihat badan diri, dan aib-aib diri, malu saya dengan panggilan “buya” itu.
Penulis: Apria Putra, MA.Hum (Filolog dan Dosen UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi)